Bukanlah Budaya, Geografi atau Pengetahuan yang menyebabkan suatu bangsa menjadi kaya atau miskin, melainkan KEMAUAN, semangat dan kerja-keras para PEMIMPIN dan rakyatnyalah yang menentukan. Silahkan baca selanjutnya …
Sub Judul: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
Penulis: Daron Acemoglu, James A. Robinson
Tebal Buku: 549 halaman
Penerbit: Crown Business, New York
Tahun: 2013
Buku ini menyajikan perbedaan-perbedaan besar, dalam hal keberhasilan dan kegagalan, antara bangsa-bangsa di negara-negara kaya, seperti AS, Inggris dan Jerman, dengan negara miskin di sub-Sahara Afrika, Amerika Tengah dan Asia Selatan.
Acemoglu dan Robinson (A&R) menawarkan sebuah teori sederhana untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu negara lebih sejahtera dibanding dengan negara lain, walaupun berdasar sejarah, budaya, geografi maupun etnis sangat mirip. Teori tersebut dimaksudkan untuk memetakan perkembangan politik dan ekonomi dunia sejak Revolusi Neolithic. Menurutnya, teori yang dipergunakan harus mampu untuk fokus menganalisis pada berbagai fenomena yang mirip, dan bisa dianggap sukses bila teori tersebut berguna dan mampu menerangkan secara empiris dan membumi, dari sebuah rangkaian proses sejarah, termasuk juga melakukan klarifikasi terhadapnya.
Teori A&R bekerja dalam dua tahap yaitu, pertama, perbedaan antara ekonomi ekstraktif dan inklusif, dan institusi-institusi politik; dan kedua adalah penjelasan mengapa institusi inklusif terjadi di beberapa negara dan tidak di tempat lain. Sementara tahap pertama teorinya tentang sejarah interpretasi institusional, tahap keduanya tentang bagaimana sejarah dapat membentuk proses institusional suatu bangsa.
Sebagai pembuka dalam bukunya, penulis menyajikan tantangan kritis berupa data tentang kesuksesan ekonomi AS. Rata-rata masyarakat AS lebih kaya tujuh kali lipat daripada kekayaan masyarakat Mexico, dan lebih dari sepuluh kali lipat dari kekayaan bangsa Peru atau America Tengah, atau duapuluh kali lipat dari masyarakat di sub Sahara, Africa. Bahkan hampir empatpuluh kali lipat dari kekayaan masyarakat di negara-negara miskin Africa, seperti Mali, Ethiopia, dan Sierra Leone.
Ada tiga hal yang pada umumnya dipergunakan sebagai alasan bahwa suatu bangsa menjadi miskin atau kaya, walaupun fakta menunjukkan hal yang berbeda, yaitu:
- Geografi
- Budaya
- Pengetahuan
1. Geografi
Montesque menyatakan bahwa bangsa yang berada di wilayah tropis cenderung menjadi bangsa pemalas yang berujung pada kegagalan ekonomi atau kemiskinan. Diapun berspekulasi bahwa seandainyapun muncul seorang pemimpin di wilayah tropis, maka akan bersikap sebagai penguasa diktator.
Teori bahwa negara-negara di wilayah tropik cenderung miskin, juga spekulasi Montesque di atas, telah terbantahkan dengan bukti begitu cepatnya pertumbuhan ekonomi di Singapura, Malaysia, dan Bostwana, yang berada di wilayah tropis. Namun demikian, masih juga ada yang menganggap bahwa iklim suatu wilayah mempunyai kaitan tidak langsung terhadap kegagalan ekonomi, karena:
- Penyakit tropis seperti malaria berkaitan dengan tingkat produktifitas
- Lahan tropis bukan lahan yang produktif/subur
Kesimpulan kedua hal tersebut tetap sama, bahwa negara di wilayah iklim sejuk relatif lebih memungkinkan untuk menjadi negara kaya daripada negara-negara di wilayah tropis atau subtropis.
Nogales, suatu wilayah yang terbelah oleh perbatasan Mexico dan Amerika Serikat menjadi bukti bahwa perbedaan kesuksesan ekonomi bukanlah karena geografi, iklim atau penyakit tetapi karena dikuasai oleh dua negara yang berbeda, yaitu Mexico dan Amerika Serikat. Demikian juga dengan fenomena perbedaan kesuksesan ekonomi antara Korea Selatan dengan Korea Utara, atau Jerman Barat dengan Jerman Timur (sebelum runtuhnya Tembok Berlin).
Sejarah lebih jauh menunjukkan bukti bahwa kemakmuran pernah terjadi di berbagai wilayah tropis pada jaman pra-modern seperti Ankor di Myanmar, Vijayanagara di India Selatan, Aksum di Ethiopia, Mihenji Daro dan Harappa di Pakistan. Ini juga berarti tidak adanya hubungan antara wilayah tropis dengan kesuksesan ekonomi.
Penyakit tropis memang menyebabkan banyak penderitaan dan tingginya kematian bayi di Afrika, tetapi bukan berarti sebagai penyebab miskinnya bangsa Afrika. Sebaliknya, wabah penyakit lebih sebagai konsekuensi yang disebabkan oleh kemiskinan atau ketidakmauan pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat.
Pendapat lain tentang Geografi sebagi faktor penyebab perbedaan kemakmuran didasarkan pada anggapan bahwa tanah tropis tidaklah produktif untuk lahan pertanian sehingga menyebabkan kemiskinan. Sebaliknya, bukti menunjukkan bahwa gagalnya pertanian di sub-Sahara Afrika pada umumnya lebih disebabkan oleh struktur kepemilikan lahan pertanian dan ketiadaan insentif pertanian dari pemerintah setempat.
Buku ini juga menunjukkan bukti-bukti bahwa besarnya kesenjangan ekonomi dunia di berbagai negara, yang diawali pada abad 19, bukankah karena perbedaan kesuksesan produktifitas pertanian seperti ditunjukkan oleh Jared Diamond dalam bukunya ‘Guns, Germs and Steels’, melainkan lebih disebabkan oleh berkembangnya teknologi industri yang dimulai dari Revolusi Industri di Inggris pada tahun 1688 (the Glorious Revolution), yang dijelaskan dengan panjang-lebar dalam bab khusus di buku ini.
Akhirnya, faktor-faktor Geografi tidak cukup kuat untuk dapat menjelaskan tidak hanya terhadap perbedaan-perbedaan kemakmuran di berbagai belahan dunia tapi juga mengapa bangsa Jepang dan Cina yang begitu lama menderita namun kemudian begitu cepat mengalami pertumbuhan ekonomi pada akhirnya. Perlu teori yang lebih handal untuk menjelaskannya.
2. Budaya
Faktor kedua yang banyak dipercaya sebagai penyebab kesuksesan ekonomi suatu bangsa adalah Budaya. Sosiolog Jerman, Max Webber, meyakini bahwa Reformasi Protestan dan etika Protestan adalah kunci penyebab tumbuhnya masyarakat industri modern di Eropa Barat. Bukti tidak membenarkan hipotesis ini. Perancis dan Itali yg dominan beragama Katolik juga menunjukkan kesuksesan ekonomi, bahkan negara-negara di Asia Timur juga bisa sukses bukan karena beragama Protestan.
Banyak yang percaya bahwa kemiskinan di Afrika disebabkan oleh rendahnya ethos kerja, tingginya kepercayaan terhadap takhyul, atau tingginya resistensi terhadap teknologi Barat. Juga, bangsa Amerika Latin tidak akan menjadi bangsa kaya karena gaya hidup masyarakatnya yang mewah namun tanpa kemampuan ekonomi. Lagi, budaya Cina, Konfusius, pada umumnya dianggap berlawanan dengan semangat pertumbuhan ekonomi. Padahal, sekarang ethos kerja Cina adalah sebagai mesin pertumbuhan ekonominya, juga Hongkong dan Singapura.
Budaya bukanlah penyebab awal perbedaan kesuksesan ekonomi, melainkan sebagai konsekuensi atau akibat dari tingkat kesuksesan ekonomi.
Tingkat kriminal yang tinggi, sebagai akibat kemiskinan, di Mexico dalam hal perdagangan narkoba menyebabkan tingkat kepercayaan sosial rendah, sehingga kebudayaan dua bangsa Nogales yang terbelah oleh perbatasan Mexico-AS menjadi berbeda. Ini adalah akibat kesuksesan ekonomi yang berbeda, bukan penyebab. Demikian juga dengan perbedaan Korea Selatan dengan Korea Utara. Semenanjung Korea mempunyai sejarah panjang kebudayaan yang sama. Sebelum perang Korea, mereka mempunyai homogenitas dalam hal bahasa, etnik dan budaya. Yang menjadi masalah adalah keberadaan batas itu sendiri dimana rejim yang berbeda menyebabkan institusi dan sistem insentif yang berbeda juga.
Bagaimana dengan Afrika? Sub-Sahara Africa adalah wilayah sangat miskin dibanding wilayah lain di dunia ini, kecuali Ethiopia dan Somalia, dan penduduknya dianggap jauh terlambat menggunakan teknologi, peralatan bertani dan budaya baca-tulis hingga akhir abad 19, meskipun bangsa Eropa telah mengarungi pantai barat Afrika di akhir abad 15 dan bangsa Asia juga telah mengarungi pantai timur Afrika di masa sebelumnya. Kongo telah melakukan kontak dengan Portugis sejak 1483, dengan Mbanza sebagai ibukota yang berpenduduk 60.000 jiwa pada tahun 1500. Tahun 1491 dan 1512, Portugis gagal mendidik bangsa Kongo untuk mengadopsi penggunaan teknologi roda dan peralatan pertanian, dan lebih memilih teknologi persenjataan. Pemilihan senjata sebagai prioritas bangsa Kongo didasari keinginan untuk menjawab kebutuhan pasar yang lebih menguntungkan, yaitu menangkap dan menjual budak.
Setelah kontak dengan bangsa Eropa lebih sering dilakukan, bangsa Afrika bisa mengadopsi berbagai budaya Barat, seperti budaya baca-tulis, mode pakaian dan desain rumah. Pada abad 19, banyak masyarakat Afrika mengambil manfaat kesempatan pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh Revolusi Industri dengan cara merubah model produksinya. Di Afrika Barat terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor minyak sawit dan kacang tanah; dan di Afrika Selatan pengembangan industri terjadi di sektor pertambangan.
Alasan utama bangsa Kongo tidak memgadopsi teknologi superior pada saat itu adalah karena tak adanya insentif dari pemerintah. Mereka menghadapi resiko tinggi akan dikenakannya sangsi atau pajak tinggi terhadap hasil produksinya oleh raja yang sangat berkuasa. Eksistensi merupakan ancaman untuk dijadikan budak oleh penguasa .
Kemiskinan akut Cina dimasa Mao juga tidak berhubungan dengan budaya Cina, tapi lebih disebabkan karena kesalahan program politik dan ekonomi Mao Zedong.
3. Pengetahuan
Kurangnya pengetahuan penguasa untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai salah satu faktor penentu gagalnya ekonomi suatu bangsa.
Suksesnya suatu ekonomi pasar adalah bila tersedia prasyarat kondisi dimana setiap individu atau perusahaan bebas untuk dapat berproduksi, menjual dan membeli setiap produk ataupun jasa yang diinginkan. Kegagalan ekonomi pasar adalah bila kondisi tersebut tidak tersedia. Ini berarti bahwa kemiskinan suatu negara terjadi karena mereka banyak mengalami kegagalan pasar, dan karena para pembuat kebijakan tidak mengerti bagaimana harus mengatasinya.
Ghana, dimasa kekuasaan Nkrumah mengalami penurunan ekonomi yang tajam sejak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Tony Killick sebagai ahli ekonomi, dikirim oleh Inggris untuk mengevaluasi kebijakan ekonominya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi Ghana tidak efisien karena pembangunan pabrik sepatu berada di lokasi yang jauh dari lokasi pemasok kebutuhan dasarnya, kulit binatang. Betulkah ini sebab utamanya? Berdasar pada prasyarat ekonomi pasar, memang terjadi kegagalan karena adanya kesulitan membeli bahan dasar industri. Namun, ini hanyalah penyebab langsung, penyebab dasarnya adalah pabrik tersebut memang harus dibangun dengan alasan transaksi politik untuk mempertahankan kelangsungan kekuasaan Nkrumah, bukan untuk kepentingan kesuksesan ekonomi bangsanya, dan bukan karena kurangnya pengetahuan.
Maka jelaslah bahwa bukan masalah kurangnya pengetahuan terhadap sistem ekonomi, melainkan karena prioritasnya jauh lebih rendah daripada kebutuhan kelanggengan kekuasaannya, dengan kata lain, tidak ada kemauan politik untuk memperbaiki nasib bangsanya. Ini hal yang sering terjadi di negara-negara dengan sistem politik ekstraktif.
Di bawah ini adalah sebagian contoh dari beberapa negara yang menjadi pokok bahasan penulis.
Inggris
Perilaku kekuasaan ekstraktif juga ditunjukkan oleh kerajaan Inggris masa Elisabeth I (1558-1603). Penemuan mesin tenun oleh William Lee yang akan dipatenkan, ditolak oleh Elisabeth I, juga James I. karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran besar-besaran yang berujung pada ketidak-stabilan politik atau goyahnya kekuasaan. Hingga abad ke-17, institusi ekstraktif Inggris sangat berkuasa, dan berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan yang tidak akan langgeng karena tidak adanya pembaruan dan hanya untuk memenuhi kepentingan sendiri.
Sejarah Inggris penuh dengan konflik antara kerajaan dengan penentangnya, antar faksi yang berebut kuasa, juga antara elit dan rakyatnya. Pada tahun 1215, para baron berhasil memaksa raja untuk menandatangani Magna Charta, yang isinya mengubah secara prinsipiil terhadap kekuasaan raja. Salah satunya, raja harus berkonsultasi dengan para baron bila akan menaikkan pajak. Langkah awal terhadap pluralisme. Konflik terus berlangsung hingga terjadi perang ‘ the war of the roses’, antara perwakilan York dengan perwakilan Lancaster untuk meraih kekuasaan raja. Lancasfer memenangkan konflik, dan Henry Tudor atau Henry VII menjadi raja Inggris pada tahun 1485.
Fokus Henry VII adalah meningkatkan sentralisasi politik. Melucuti persenjataan istana atau demiliterisasi, yang berarti memperkuat kekuasaan pemerintah pusat. Sentralisasi kekuasaan ini juga berarti untuk pertama kalinya pemerintah Inggris berpotensi untuk menjadi pemerintahan yang inklusif. Proses ini dimulai oleh Henry VII dan Henry VIII, yang tidak hanya sentralisasi kekuasaan tetapi juga tuntutan representasi kekuasaan untuk masyarakat yang lebih luas. Konflik terus terjadi setelah kekuasaan Henry VIII dan institusi ekstraktif kembali muncul pada dinasti berikutnya.
Tahun 1688 adalah tahun yang sangat penting bagi Inggris, dimana kekuasaan ekstraktif dibawah kekuasaan raja James mulai digantikan oleh William dan parlemen juga sudah mulai kuat. The Glorius Revolution menghasilkan the Declaration of Rights yang dibuat oleh paelemwn dan raja William di tahun 1689, yang salah satu isinya adalah tentara hanya bisa digerakkan dengan sepwngwtahuan parlemen. Raja bahkan bersedia untuk tidak menginerfensi kekuasaan sistem hukum. Perubahan institusi politik yang lebih inklusif dengan dengan snemakin kuatnya kekuasaan parlemen, menunjukkan akhir dari kekuasaan absolut raja.
Setelah 1688, Parlemen mulai dapat meningkatkan pendapatan dari pajak, juga memperkuat institusi infrastruktur pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan yang lebih pluralistik.
Revolusi Industri sangat mempengaruhi dalam setiap aspek ekonom Inggris, khususnya dibidang transportasi, metalurgi dan mesin uap. Mekanisasi dan pabrikasi produksi tekstil adalah bidang utama yang sangat menonjol. Ini bukan hanya karena munculnya larangan monopoli domestik tetapi lebih karena adanya reorganisasi fundamenfal terhadap institusi ekonomi seiring munculnya banyak pengusaha dan penemuan baru serta perlindungan terhadap keamanan hak-hak kepemilikan. Adalah the Glorious Revolution yang menyebabkan sistem politik Inggris menjadi inklusif, terbuka dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan aspirasi masyarakat.
Maluku
Buku ini juga sedikit menyinggung tentang Indonesia, khususnya kepulauan Maluku. Pada awal abad 17, kepulauan Maluku terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah utara dengan kerajaan Ternate, Tidore dan Bacan, kemudian kerajaan Ambon di bagian tengah, dan wilayah selatan adalah kepulauan Banda yang masih belum ada pemerintahannya. Meskipun saat ini kepulauan Maluku terasa jauh dari pusat pemerintahan RI, saat itu sudah sangat terkenal di perdagangan dunia sebagai penghasil dan eksportir rempah-rempah, seperti cengkeh dan pala. Sebaliknya, impor bahan makanan dan produk pabrikan diperoleh dari pulau Jawa, Malaka (pantai barat Malaysia), India, China dan Arab.
Kontak pertama dengan bangsa Eropa terjadi pada awal abad 16, pelaut Portugis, yang membeli rempah-rempah dan selanjutnya berupaya untuk menguasainya. Malaka, lokasi strategis lalulintas perdagangan Asia Tenggara, yang berada di pantai barat semenanjung Malaysia, pada tahun 1511 dikuasai Portugis. Perkembangan ekonomi Asia Tenggara pada abad 14-16 cukup bagus karena didukung oleh perdagangan rempah-rempah di Aceh, Banten, Malaka, Makassar dan Brunei.
Seperti halnya kekuasaan di Eropa pada jamannya, raja-raja di Asia Tenggara pun menerapkan budaya kekuasaan yang sama, absolut. Pertumbuhan ekonomi tinggi, namun jauh dari kesejahteraan rakyatnya. Belanda masuk ke Ambon pada tahun 1600 dengan cara membuat perjanjian eksklusif dengan para penguasa setempat yang memberinya kekuasaan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan berdirinya Dutch East India Company pada tahun 1602, Belanda telah menguasai perdagangan semua rempah-rempah dan menghempaskan para pesaingnya, by hook or by crook, yang terbaik untuk Belanda dan sebaliknya untuk Asia Tenggara.
Ambon diperlakukan dengan kejam oleh Belanda, persis seperti perilaku Eropa dan Amerika pada saat itu. Kerjapaksa diberlakukan pada rakyat Ambon untuk menghasilkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Belanda juga menguasai kepulauan Banda untuk cengkeh dan pala. Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Batavia, pada tahun 1621 membantai hampir semua penduduk kepulauan Banda, kurang-lebih 15.000 orang, untuk mengamankan pengetahuan cara memproduksi cengkeh dan palawija. Para pekerja-paksa baru ditempatkan untuk dilatih berkebun cengkeh dan palawija.
Pada akhir abad ke-17, Belanda mengurangi 60% pasokan rempah-rempahnya ke seluruh dunia namun harga palawija naik dua kali lipat. Strategi yang sama coba diterapkan Belanda di wilayah Asia Tenggara lainnya, namun pembangkangan mulai terjadi akibat kesewenang-wenangan. Ekspansi ekonomi yang sudah berlangsung lama, abad 14-16, mulai menunjukkan titik balik. Tahun 1620, Banten merusak sendiri kebun merica dengan harapan Belanda meninggalkannya dengan damai. Tahun 1686, kerajaan Naguindanao, Philipina, merusak sendiri perkebunan rempah-rempahnya dan menolak berkebun merica di tahun 1699. Bahkan deurbanisasi dilakukan oleh rakyat Burma dari wilayah Pegu untuk menolak bekerja di perkebunan pada tahun 1635.
Seperti halnya di Maluku, kolonialisme Belanda telah menyebabkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi politik di Asia Tenggara, yang menghentikan produksi rempah-rempah, menutup diri dan bahkan semakin absolut. Dua abad setelahnya, Asia Tenggara tidak dapat turut mendapatkan keuntungan dari keberadaan Revolusi Industri. Celakanya, mogok bekerjasama dengan Eropa tetap tidak dapat menyelamatkannya bahkan pada akhir abad 18 hampir semuanya di Asia Tenggara berada dalam penjajahan Eropa.
Ketika industrialisasi menyebar ke sebagian wilayah dunia, wilayah-wilayah dibawah kekuasaan kerajaan kolonial Eropa tetap tidak dapat mengambil keuntungan dari munculnya banyak teknologi baru di era Revolusi Industri. Wilayah yang sebelumnya mempunyai keunggulan ekonomi menjadi miskin karena perilaku ekstraktif pemerintahnya.
Australia
Inggris Raya (Wales, Scotland dan England) pada tahun 1707 memutuskan untuk memindahkan para narapidana kriminal ke koloninya yang jauh dari tempat asalnya. Setelah kemerdekaannya pada tahun 1783, AS menolak untuk menerima pindahan penduduk dari Inggris Raya. Kapten James Cook mendarat di Botany Bay, Sidney (sekarang), Australia, 29 April 1770 dan merekomendasikan tempat yang bagus ini untuk para narapidana Inggris Raya. Dibawah komando Kapten Arthur Phillip, sebelas kapal pengangkut narapidana mendarat di Botany Bay pada Januari 1788, kemudian membangun penampungan di Sydney Cove,- pusat kota modern Sydney -, dan menyebutnya koloni ini sebagai New South Wales serta menentukan tanggal 26 Januari sebagai Australia Day.
Mengingat bekerja dalam paksaan tidak akan menghasilkan produksi yang memuaskan, maka para narapidana diberi kesempatan untuk bekerja diluar jam kerja-paksa dan dapat menjual produknya untuk dirinya sendiri. Para narapidana bahkan bisa menjadi pengusaha dan mempekerjakan narapidana lain bahkan diberikan tanah setelah selesai masa penahanannya.
Tuntutan mulai muncul dari para ex-narapidana dan keluarganya yang dipimpin oleh William Wentworth, akan institusi politik yang lebih inklusif, perwakilan politik, perlu adanya juri dalam permasalahan hukum terhadap ex-narapidana dan keluarganya serta diberhentikannya pengiriman narapidana dari Inggris Raya ke New South Wales. Pada tahun 1840, pengiriman narapidana dihentikan dan pada 1842 duapertiga anggota legislatif dipilih oleh rakyat. Ex-narapidana berhak dipilih menjadi anggota legislatif apabila mempunyai cukup properti.
Seperti halnya Amerika Serikat, Australia mempunyai pengalaman yang berbeda dengan Inggris dalam mendapatkan institusi yang inklusif. Inggris membutuhkan terjadinya revolusi besar Perang Sipil dan Glorious Revolution yang tidak terjadi di Australia dan AS karena lingkungan politik yang berbeda. Inggris mengalamu sejarah kepemimpinan absolut yang panjang sehingga membutuhkan usaha besar untuk merubahnya. Revolusi Perancis mempercepat kemakmuran di Australia dan AS, yang telah siap dengan institusi inklusifnya.
Perancis
Hingga 1789, sudah tiga abad Perancis dibawah pemerintahan monarkhi absolut. Masyarakat Perancis terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kaum bangsawan, pegawai pemerintah dan masyarakat umum. Aristokrat dan pegawai pemerintah tidak membayar pajak, sedangkan masyarakat umum wajib membayarnya. Jelas nerupakan pemerintahan yang bersifat ekstraktif. Hukum tidak hanya menjamin kesejahteraan ekonomi bagi kaum bangsawan dan pegawai pemerintah, namun juga kekuasaan politik.
Dalam situasi Revolusi Perancis, 4 Agustus 1789, Dewan Konstitusi Nasional mengubah hukum Perancis dengan konstitusi baru, yang pada dasarnya menghilangkan pemerintahan monarkhi absolut. Beberapa pasalnya menyebutkan: meghapuskan sistem feodal, pajak dikenakan terhadap semua penduduk tanpa memperdulikan status sosial seseorang, termasuk bangsawan dan pegawai pemerintah.
Beberapa puluh tahun kemudian, Perancis dalam kondisi instabilitas sebagai akibat deklarasi 4 Agustus tersebut, namun langkah penghapusan absolutisme dan institusi ekstraktif menuju sistem politik dan ekonomi yang inklusif sudah tidak mungkin mundur lagi.
Tentara revolusioner Perancis dibawah Napoleon dengan cepat melakukan reformasi secara radikal untuk menghapuskan feodalisme dan perbudakan; serta kesetaraan didepan hukum di semua wilayah yang ditaklukkan, yang dikenal dengan Napoleon Code.
Pada pertengahan abad ke sembilan belas, industrialisasi menyebar cepat hampir ke semua wilayah Eropa yang dikuasai Perancis, kecuali wilayah Austria-Hungaria dan Rusia yang bukan wikayah kekuasaan Perancis; atau Polandia dan Spanyol dimana Perancis hanya menguasai sementara saja, tetap dibawah institusi negara yang ekstraktif.
Jepang-Cina
Sebelum Restorasi Meiji 1868, secara ekonomi, Jepang termasuk negara belum berkembang dibawah kontrol shogun keluarga Tokugawa sejak 1600. Shogun adalah kelompok sosial dominan feodalistik, semacam tuan tanah (penguasa sipil), yang sangat berkuasa dimasyarakat, sementara raja hanyalah seremonial belaka. Shogun Satsuma, yang dikuasai keluarga Shimazu, berkuasa di wilayah selatan. Berbeda dengan Tokugawa, dibawah shogun Satsuma, perdagangan antar negara diperbolehkan. Dimulai dari kekuasaan shogun Satsuma yang didukung banyak pihak inilah berujung pada tergulingnya kekuasaan ekstraktif Tokugawa dan kembali pada kekuasaan tunggal raja Komei, yang wafat setelah satu bulan Restorasi Meiji dideklarasikan (3 Januari 1868). Meiji, putra Komei, menggantikannya, dan sejak itu politik dan ekonomi inklusif diterapkan.
Pada tahun 1869, kesetaraan didepan hukum mulai diperkenalkan, serta pembatasan migrasi dan perdagangan juga tidak diperkenankan. Pemerintah mulai banyak terlibat pembangunan infrastruktur, mulai dari pengembangan jalur kapal uap Tokyo-Osaka, pembangunan jalan keretaapi Tokyo-Yokohama, industri manufaktur terus dikembangkan dan impor mesin tekstil dilakukan untuk modernisasi pembuatan kain katun.
Seperti halnya dengan Jepang, Cina adalah negara miskin pada pertengahan abad 19, karena rejim absolut. Demikian juga halnya Jepang yang dimasa Tokugawa melarang perdagangan antar negara pada abad 17, kekuasaan dinasti Cina telah mulai melakukan hal yang sama lebih awal dan menentang perubahan politik dan ekonomi. Perbedaannya adalah, birokrasi Cina terpusat dibawah kekuasaan absolut kerajaan (bukan penguasa sipil), bersifat ekstraktif dan sulit untuk dirubah, walaupun pemberontak sering terjadi. Sementara Jepang dibawah shogun Satsuma, menyadari sepenuhnya bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai dengan reformasi institusi dan kekuasaan shogun harus dibubarkan. Alih-alih melakukan reformasi institusi, pemerintah Cina malah impor senjata modern dari Inggris untuk mempertahankan kekuasaannya, sementara Jepang justru mengembangkan sendiri industri senjatanya.
Sebagai konsekuensi dari perbedaan mendasar pada karakter institusinya, Cina dan Jepang memberikan respon yang sangat berbeda terhadap tantangan titik kritis Revolusi Industri abad 19. Sementara institusi Jepang mulai berubah lebih inklusif dan ekonomi menjadi tumbuh dengan cepat, desakan perubahan di Cina tidak cukup kuat bahkan semakin buruk pada masa Revolusi Kebudayaan di masa Mao.
Kesimpulan
Contoh-contoh di atas bermaksud menjelaskan bahwa bukanlah Budaya, Geografi atau Pengetahuan yang menyebabkan suatu bangsa menjadi kaya atau miskin, melainkan kemauan, semangat dan kerja-keras para pemimpin dan rakyatnyalah yang menentukan.
Perbedaan sukses ekonomi yang terjadi di berbagai negara disebabkan oleh institusi-institusi dan aturan-aturannya yang mempengaruhi jalannya ekonomi, serta insentif terhadap bangsanya.
Pertumbuhan dibawah institusi ekstraktif tidak akan berlangsung lama, karena:
- Pertumbuhan ekonomi yang langgeng (menerus) membutuhkan adanya inovasi, yang berdampak distruktif kreatif sehingga menggantikan sistem ekonomi yang lama dengan yang baru, dan juga mendestabililisasi relasi kekuasaan politik yang ada
- Kekuasaan politik yang mampu mendominasi institusi ekstraktif untuk mengambil untung dari para pihak yang kalah, berakibat munculnya keinginan banyak pihak untuk melakukan perebutan kekuasaan.
Perubahan besar institusional merupakan syarat terjadinya perubahan besar ekonomi, yang terjadi sebagai akibat interaksi antara institusi yang ada dengan kondisi kritis (critical junctures). Kondisi kritis dimaksud adalah perubahan-perubahan besar yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan baru antara politik dan ekonomi didalam satu masyarakat atau lebih. Misalnya, peristiwa Black Death, yang menewaskan setengah populasi hampir seluruh Eropa selama abad 14M; pembukaan rute perdagangan Atlantis yang menghasilkan keuntungan besar masyarakat Eropa Barat; dan Revolusi Industri yang menyebabkankan perubahan positif, besar dan cepat dalam hal struktur ekonomi dunia.
Kritik
- Buku ini cukup rumit untuk dibaca, bukan karena bobot isinya, melainkan karena penyajian yang tidak sistematis. Beberapa contoh negara dibahas dalam beberapa bab yang terpisah-pisah, sehingga seringkali harus membalik-balik bab sebelumnya untuk mengetahui alur sejarahnya.
- Banyak kalimat yang sering diulang di beberapa bab, khususnya tentang pengertian dan dampak institusi ekstraktif/inklusif.
- Banyak pengetahuan bisa diperoleh dari buku ini, khususnya tentang sejarah dunia dan sosio-ekonominya.
- Bagus untuk dibaca oleh siapapun yang peduli tentang kemajuan bangsanya
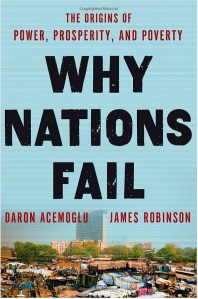


[…] kesimpulan Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam bukunya ‘Why Nations Fail’ https://anangsk.wordpress.com/2013/11/17/mengapa-ada-negara-kaya-dan-miskin/ . Semoga kebisingan politik di tahun 2015 sudah mereda dan bersama-sama lebih fokus untuk meraih […]